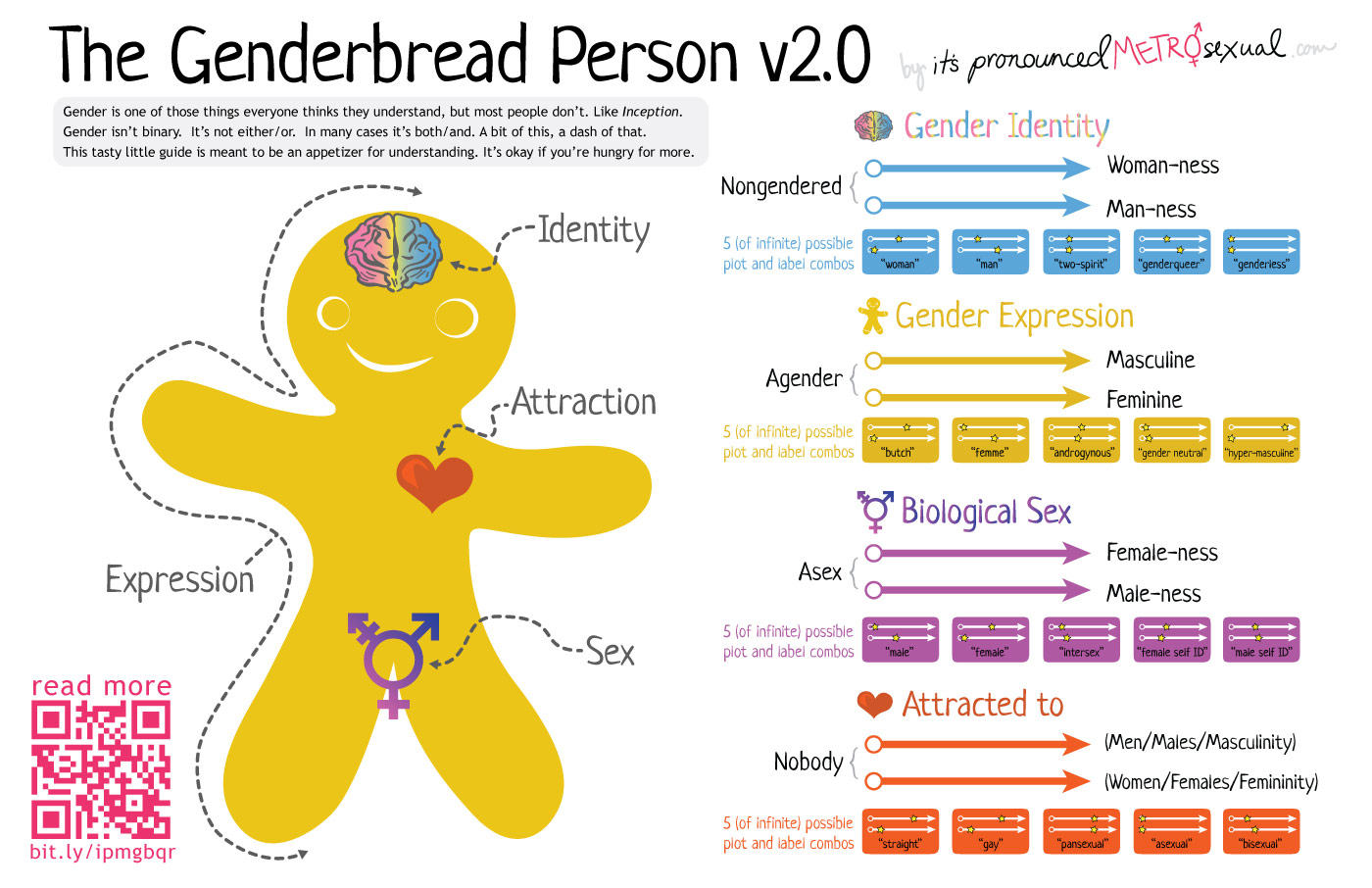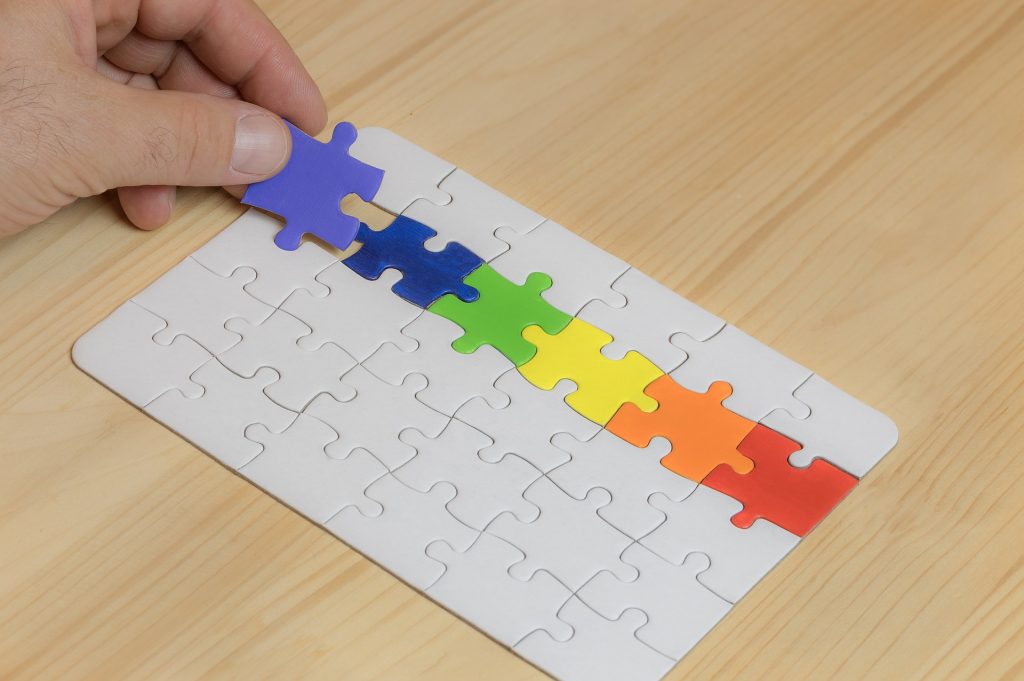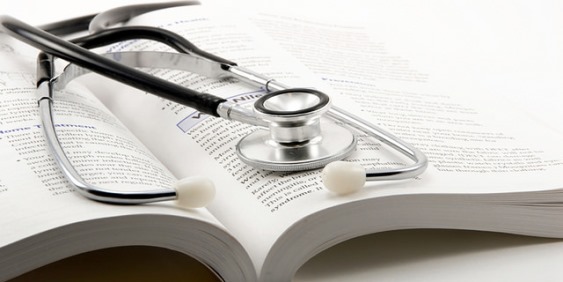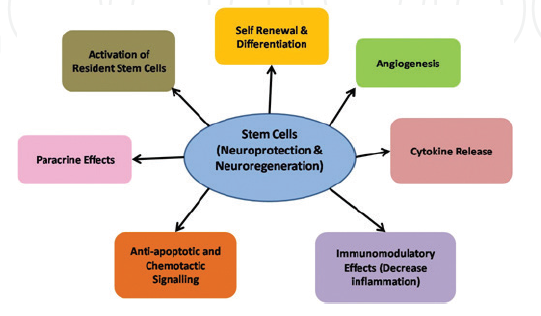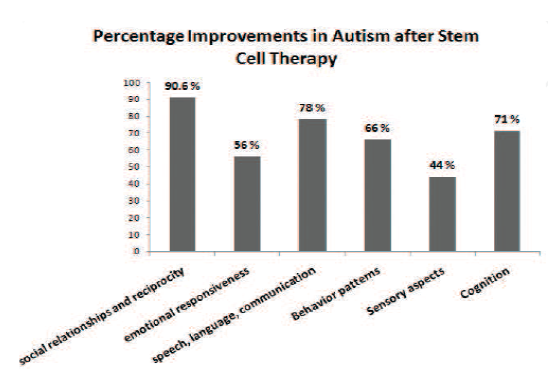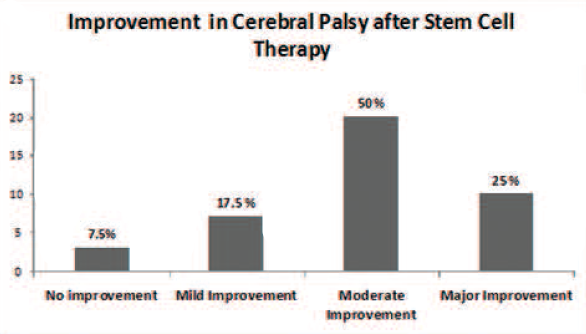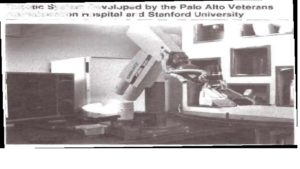Memulai Hubungan dari Hal Sederhana

Sering kali kita mendengar klien berkata “Melihat terapis nya ramah senyum saja sudah mengurangi separuh nyeri saya”, atau kata seperti “Saya selalu semangat datang terapi, karena mbak dan mas terapis nya memotivasi saya dengan baik”.
Ternyata belum melakukan tindakan intervensi yang jauh saja sudah membuat klien kita merasa sedikit lebih baik. Menjadi tenaga kesehatan memang menguras tenaga baik fisik maupun emosional.
Namun, menjadi klien yang mengalami disfungsi menguras tenaga fisik dan emosional untuk datang mengakses layanan kesehatan pula. Maka kita terapis harus bisa menjadi professional dan melayani sepenuh hati.
Pada tahun 1913, Sigmund Freud berhipotesis bahwa hubungan antara terapis dan pasien adalah komponen kunci dari pengobatan yang sukses. Sejak saat itu, penelitian telah menunjukkan bahwa kualitas hubungan ini (‘aliansi terapeutik’ seperti yang disebut) merupakan prediktor terkuat keberhasilan terapi (Knobloch, 2008).
Lalu bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara terapis dan klien secara profesional? Sebelum sampai kesana, mari kita belajar manfaat dari menjalin hubungan yang baik dengan klien.
Manfaat memiliki Hubungan yang Baik dengan Klien
Dapat memunculkan kolaborasi yang baik antara klien dan terapis
Kolaborasi yang baik dapat membuat kita berada pada satu jalan dengan klien. Tanpa kolaborasi yang baik, seperti klien yang hanya menggantungkan pada terapis tanpa melakukan home program yang diberikan, terapis yang tidak memberikan umpan balik saat klien berkeluh kesah maka proses terapi yang dijalankan pun akan terasa sulit.
Dalam setting pediatri, kolaborasi pertama terjadi antara terapis, orang tua dan anak. Tetapi, kolaborasi paling awal yang harus dibangun dalam setting pediatri adalah antara terapis dan orang tua. Kolaborasi antara terapis dan orangtua yang kuat dapat meningkatkan rasa pemahaman, harapan dan rasa syukur terhadap anak.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baiknya hubungan kolaborasi tersebut berimplikasi sangat kuat dan meningkatkan efektivitas proses terapi yang dijalankan, sehingga outcome yang dihasilkan dalam terapi pun lebih baik (Feinstein, Udvari-Solner & Joshi, 2009).

Meningkatkan kualitas komunikasi yang dijalin
Saat kita memiliki hubungan baik dengan klien, maka akan mudah sekali dalam menjalin komunikasi. Melalui komunikasi yang terjalin dengan baik, terciptalah hubungan emosi yang kuat. Sehingga klien lebih leluasa menyampaikan keluhan dan harapannya.
Penelitian menunjukan hubungan yang baik dapat membuat klien lebih terbuka dan jujur dalam menyampaikan respon emosi negative yang dialami dan juga dapat menyelesaikan permasalahan negative yang dialami lebih baik (Knobloch, 2008).
Dapat menuntun ke hasil terapi yang lebih baik
Berdasarkan meta analysis pada aspek hubungan terapi tentang hubungan berbasis bukti & responsif, ditemukan bahwa sejumlah faktor hubungan, seperti menyetujui tujuan terapi, mendapatkan umpan balik klien selama perawatan dan memperbaiki masalah klien secara bersama memberikan hasil yang positif karena membantu dalam penggunaan metode perawatan yang tepat kepada klien (Deangelis, 2019).
Bagaimana Membangun Hubungan Terapetik dengan Klien?
Saat berbicara tentang hubungan terapetik Secara historis, studi tentang hubungan terapeutik hanya berfokus pada hubungan pasien dengan terapis. Namun, penelitian yang dilakukan di The Family Institute di Northwestern University dan Dr. William Pinsof (2019) menunjukkan pentingnya memperluas definisi ini untuk memasukkan pengaruh orang lain yang signifikan dalam kehidupan pasien seperti anggota keluarga, pasangan, teman dekat.
Penelitian yang dilakukan Knobloch (2008) tentang Pentingnya Hubungan dengan Terapis memaparkan bahwa cara menciptakan hubungan yang baik antara terapis dan klien adalah membangun empati dan pemahaman, menciptakan rasa keterbukaan, memiliki fleksibilitas dan kemauan beradaptasi dengan klien. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun hubungan terapetik bersama klien :

Bangun rasa empati dan memahami klien
Saat awal terapis bertemu klien, hal yang harus kita bangun adalah rasa empati dan memahami keadaan dan perasaan klin kita, bukan apa masalah klien dan apa tujuan terapi yang bisa diberikan. Saat awal-awal pertemuan, ibaratkan kita (terapis) adalah seseorang yang bertamu di suatu rumah baru.
Sangat tidak etik bukan jika kita langsung mengunjungi dapur tanpa mengenal ruang depan? Begitu pula dengan klien, klien akan merasa tidak nyaman jika kita langsung terjun ke dalam tanpa berkenalan dan membangun rasa saling memahami.
Berdasarkan pengalaman saya, saya selalu berusaha membangun empati dan memahami klien saat awal-awal klien menjalankan terapi, seperti memahami apa yang klien suka dan tidak suka, apa yang membuat klien bersemangat, apa yang membuat klien tidak nyaman & tidak memaksakan klien untuk melakukan aktivitas yang kita minta dan berikan.
Oleh sebab itu, klien akan menunjukan kepercayaan terhadap kita karena merasa aman dan nyaman dengan kita sebagai terapis sehingga proses terapi yang dijalankan pun menjadi lebih baik.
Ciptakan Keterbukaan
Keterbukaan sangat penting saat membangun hubungan terapetik dengan klien. Saat dengan klien dewasa, terapis diharapkan dapat terbuka dengan tujuan & proses terapi yang akan dijalankan. Sehingga klien tidak merasa seperti sebuah objek yang di otak-atik oleh terapis, namun bisa merasa menjadi seorang “partner” yang bersama-sama menuju tujuan yang sama.
Dalam setting pediatri, keterbukaan sangat perlu terjalin dengan orang tua dan juga anak. Menciptakan keterbukaan dapat dilakukan seperti menyampaikan pada orang tua bagaimana permasalahan anak, dan bagaimana cara yang dapat dilakukan bersama agar mendapatkan hasil yang memuaskan.
Maka sangat penting mengkomunikasikan hasil terapi di setiap setelah pertemuan, seperti apa yang telah dapat dicapai anak hari ini dan bagaimana cara memaksimalkan potensi anak dirumah melalui home program.
Fleksibilitas dan kemauan untuk beradaptasi dengan klien
Kondisi klien tidak dapat kita prediksi di setiap pertemuan. Pada beberapa kasus pediatri, emosi anak masih turun-naik seperti saat dirumah anak merasa baik-baik saja namun saat tiba di ruangan terapi anak merasa cemas. Begitu pula klien dewasa fisik maupun psikososial, pertemuan sebelumnya klien merasa bersemangat dan termotivasi, bisa jadi pertemuan kali ini klien merasa murung dan tidak bersemangat.
Fleksibilitas
Maka disinilah peran terapis, agar terciptanya hubungan yang baik dan klien dapat lebih mudah mengkomunikasikan perasaan negatif nya, terapis diharapkan menjadi pribadi yang fleksibel dan dapat beradaptasi.
Salah satu bentuk dari fleksibilitas adalah dengan cara tidak memaksakan program terapi yang sudah kita susun di hari itu terhadap klien saat klien tidak dalam kondisi baik. Meskipun klien harus mencapai tujuan yang telah disepakati, namun perasaan dan apa yang dialami klien di hari itu adalah lebih penting.
Kemauan Beradaptasi
Kemauan beradaptasi dengan klien dapat dilakukan dengan cara mengubah aktivitas yang sesuai dengan keadaan klien dihari itu juga, contoh nya klien anak yang minggu lalu sudah berfokus dalam meningkatkan kognitif karena hari ini anak mengalami cemas berlebih maka kita harus dapat mengubah aktivitas kearah calming bagi anak.
Hal tersebut dapat membuat klien merasa bahwa kita dapat beradaptasi dengan merasa dalam situasi apapun yang sedang mereka alami dan tidak menjadi pribadi yang kaku serta memaksakan.

Kesimpulan
Banyak klien yang saat sebelum mengakses terapi mereka berpikir “apakah mengikuti terapi ini akan benar-benar berguna bagi diriku?”. Penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor mempengaruhi apakah sebuah pengobatan akan berhasil, seperti tingkat keparahan masalah yang sedang diobati, keyakinan pasien bahwa treatment akan bekerja dan tingkat keterampilan terapis.
Namun, penelitian selama lima puluh tahun terakhir telah menunjukkan bahwa satu faktor, lebih dari yang lain, dikaitkan dengan pengobatan yang sukses yaitu kualitas hubungan antara terapis dan pasien. Maka, inilah betapa pentingnya menciptakan hubungan terapetik dengan klien agar outcome yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.
Referensi
Knobloch-Fedders, L. (2008). The importance of the relationship with the therapist. Clinical Science Insights, 1, 1-4. https://www.family-institute.org/behavioral-health-resources/importance-relationship-therapist
Pinsof, W. M. (2019). Family Institute at Northwestern University. Encyclopedia of Couple and Family Therapy, 1061-1068.
Deangelis, T. O. R. I. (2019). Continuing Education: Better relationships with patients lead to better outcomes. Monitor on Psychology, 50(10). https://www.apa.org/monitor/2019/11/ce-corner-relationships
Feinstein, N. R., Fielding, K., Udvari-Solner, A., & Joshi, S. V. (2009). The supporting alliance in child and adolescent treatment: Enhancing collaboration among therapists, parents, and teachers. American Journal of Psychotherapy, 63(4), 319-344.